Ibdati Malika, seorang pasien a schizoaffective bipolar II disorder, menceritakan perjalanannya dalam melawan kondisinya, bagaimana dia bertahan, dan apa arti support baginya.
Ibdati Malika, seorang pasien a schizoaffective bipolar II disorder, menceritakan perjalanannya dalam melawan kondisinya, bagaimana dia bertahan, dan apa arti support baginya.
Jadi gimana ceritanya pertama kali curiga tentang penyakitmu?
Sebetulnya awalnya aku merasa tidak ada apa-apa. Tapi orang-orang disekelilingku yang banyak protes “Kok kamu jadi suka marah-marah, Lik?”. Dan dimata mereka, ketika aku jawab pertanyaan itu, aku makin marah-marah lagi. Awalnya aku tidak gubris dan anggap itu biasa saja. Tapi beberapa bulan kemudian, suatu hari di kampus aku sedang dinyinyirin oleh teman, dan tiba-tiba timbul keinginan untuk melukai mereka dengan gunting. Aku sama sekali tidak sadar sampai tiba-tiba gunting itu diambil temanku yang lain. Besoknya, tiba-tiba aku berhalusinasi mendengar suara-suara aneh yang aku tahu harusnya tidak aku dengar. Saat itulah aku benar-benar panik dan langsung mencari bantuan untuk bertemu dengan psikolog.
Lalu kapan diagnosis keluar?
Pertama kali ketemu psikolog, aku menjalani yang namanya anamnesis (pemeriksaan riwayat kesehatan). Disitu aku diminta untuk memperkenalkan diri dari segala aspek, mulai dari identitas, apa yang aku alami, dan harapan aku dengan menjalankan terapi ini seperti apa. Uniknya, karena didorong rasa takut, aku sama sekali tidak merasa terganggu untuk menceritakan hal sepribadi itu ke psikolog yang notabene adalah orang asing dimataku. Rasa takut ini muncul karena aku sebagai artist memang sering melakukan riset mengenai kesehatan mental untuk karakter-karakter novel yang aku tulis, sehingga aku tahu bahwa penyakit mental adalah betul-betul penyakit yang harus diobati. Aku termotivasi kalau aku tidak boleh terjerumus semakin dalam. Setelah diagnosis dari psikolog sudah keluar, aku dirujuk ke psikiater. Disitulah aku tahu bahwa aku ternyata mengidap schizoaffective bipolar disorder II tipe depresi dan mania.
Bagaimana perasaanmu saat mendengar diagnosis?
Aku merasa takut. Tapi sebetulnya perasaan yang paling dominan adalah perasaan hancur saat aku harus menjelaskan tentang penyakit yang aku punya ini ke orang tua, karena gw merasa mengecewakan mereka.
Bagusnya, aku sangat termotivasi untuk sembuh. Dalam diagnosis kategori penyakitku masih prodromal (tahap awal). Psikologku menekankan kalau aku bisa sembuh tapi harus konsisten. Ini salah satu pelajaran yang aku pelajari selama menjalankan terapi, konsisten itu kuncinya. Kalau mau sembuh ya harus konsisten dan disiplin. Penanganan penyakit mental itu tidak hanya pasif, tapi aktif. Artinya dari pasien sendiri harus ada kemauan.
Bagaimana cerita perjalanan terapi kamu?
Setelah sampai di psikiater, beliau kembali bertanya tentang riwayat kesehatanku. Setelah itu aku di preskripsikan obat dan diminta untuk kembali atau mengabari perkembangan ke dokter setelah obat habis, yaitu sekitar satu bulan berikutnya. Selain itu, aku juga menjalankan terapi kognitif perilaku (CBT) untuk mengatasi mood aku, khususnya untuk mengalihkan pengekspresian marah dari diri aku. Waktu itu aku terapi dengan menggambar menggunakan cat air (pakai sesuatu yg lembut seperti kuas dibanding hal berujung tajam seperti pena) dan menulis diary untuk mengontrol emosi.
Pertama minum obat gimana rasanya?
Aku sebetulnya beruntung, karena aku langsung dapat obat yang cocok. Banyak teman-temanku yang butuh bertahun-tahun untuk dapat obat yang cocok untuk mereka.
Tapi, rasa efek sampingnya benar-benar tidak enak, terutama efek samping berupa kabut otak. Aku jadi susah diajak bicara dan tidak fokus. Untuk efek samping fisik itu masih bisa aku atasi, yang parah sebetulnya adalah tekanan dari orang sekitar.
Seharusnya, aku terapi selama 1.5 tahun. Tapi setelah 1 tahun aku memutuskan untuk berhenti terapi. Alasan aku berhenti adalah karena aku tidak tahan dengan diskriminasi dan cemooh dari orang sekitar. Aku bahkan dituduh kalau aku pemakai narkoba, atau dituduh berlindung dibalik penyakit aku untuk menghindari tanggung jawab. Karena tekanan ini, aku memutuskan untuk berhenti berobat dan bilang ke keluargaku kalau aku sudah sembuh dan baik-baik saja.
Efeknya, penyakitku kambuh beberapa bulan kemudian.
Apa hal yang sebetulnya membantu kamu untuk berjuang atau merasa lebih baik?
Kalau yang aku lihat dari sekelilingku, sebetulnya 60% dari mereka supportive, 30% dari mereka mencemooh, dan 10% sisanya tidak peduli. Selalu ingat, kalau omongan bisa menghancurkan, omongan juga bisa menyembuhkan. Jadi jangan cepat menilai atau mencemooh, menyemangati itu sudah lebih dari cukup.
Hal lain yang suka aku lakukan adalah melakukan hal yang meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya untuk aku pribadi, dengan menari, melukis, atau sekadar lompat-lompat. Kadang ada titik dimana aku merasa ingin menyakiti diri sendiri untuk menyalurkan rasa sedih dan frustasiku tentang keadaanku, tapi dengan menyalurkan ke hal lain yang membuat aku merasa berguna, itu membuat aku merasa lebih baik.
Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk kita semua tentang kesehatan mental?
Jangan cepat mengejek tentang hal yang kamu “mungkin” tidak punya pengetahuan yang cukup. Semua orang sedang berusaha mengerti apa yang terjadi dari berbagai aspek. Menilai hanya dari satu sisi itu bukan hal yang bijak untuk dilakukan, apalagi mengejek.
Ibdati Malika has consented to the content of the article and given permission to publish her story with her full name.

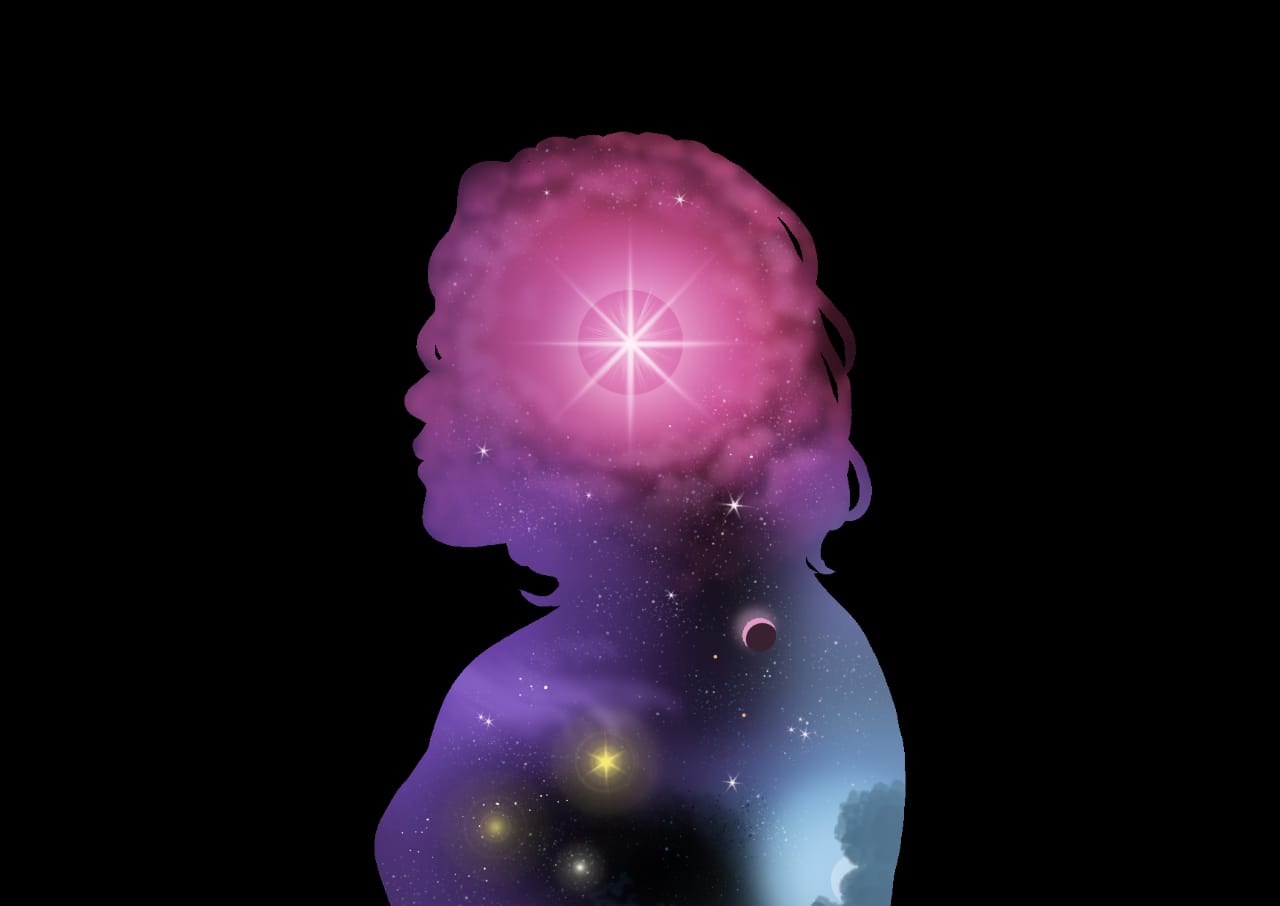



Leave a Comment